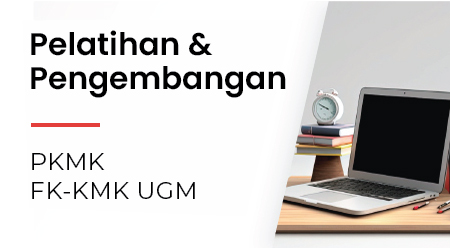DI seluruh belahan dunia, sistem kesehatan terus menghadapi tantangan kompleks, dan salah satu yang paling krusial adalah masalah pembiayaan. Pada tataran global, perubahan epidemiologi penyakit, peningkatan beban penyakit tidak menular (PTM), serta tekanan ekonomi pascapandemi COVID-19 telah mendorong negara-negara untuk menata ulang sistem pembiayaan kesehatannya. Bahkan negara-negara dengan sistem kesehatan yang kuat pun tidak luput dari tekanan finansial dalam menjaga keberlanjutan layanan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara konsisten menekankan pentingnya negara-negara mengembangkan sistem pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan.
Indonesia, dalam konteks tersebut, telah melakukan langkah besar dengan mengimplementasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 2014. Program ini berupaya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), dengan prinsip pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dengan jumlah peserta aktif mencapai lebih dari 250 juta jiwa, JKN menjadi salah satu sistem asuransi kesehatan sosial terbesar di dunia. Namun besarnya skala sistem ini membawa konsekuensi berupa kompleksitas pengelolaan dan tantangan dalam keberlanjutan pembiayaan.
Setiap tahun, pembiayaan JKN membutuhkan subsidi dari pemerintah pusat dalam jumlah yang besar. Laporan dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa klaim pelayanan kesehatan, khususnya untuk penyakit katastropik seperti gagal ginjal kronis, kanker, dan penyakit jantung, menyerap sebagian besar anggaran. Meski demikian, biaya preventif dan promotif sering kali masih mendapatkan porsi yang lebih kecil. Padahal, untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan tahan banting, investasi pada upaya pencegahan penyakit menjadi sangat krusial.
Dalam konteks desentralisasi, peran pemerintah daerah menjadi penting dalam mendukung sistem pembiayaan kesehatan. Aceh, sebagai provinsi yang memiliki kekhususan dan mendapatkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus), seharusnya memiliki ruang fiskal yang relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain. Sejak awal pelaksanaan JKN, Aceh sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang bahkan lebih dulu hadir sebelum BPJS Kesehatan diluncurkan secara nasional. Program JKA pernah menjadi rujukan karena menjamin pelayanan kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat Aceh, tanpa melihat status ekonomi.
Namun, setelah integrasi JKA ke dalam JKN, tantangan mulai muncul. Perubahan mekanisme pembiayaan, klaim, dan pengelolaan data memerlukan adaptasi dari berbagai pihak, mulai dari fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, hingga pengambil kebijakan. Tidak jarang ditemui adanya keterlambatan klaim, tumpang tindih data, dan kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang tersedia di lapangan. Beberapa rumah sakit di Aceh sempat menghadapi tekanan operasional karena belum cairnya pembayaran klaim dari BPJS dalam waktu yang cepat, terutama rumah sakit di daerah yang bergantung penuh pada sistem klaim.
Di sisi lain, keberadaan dana Otsus belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat sistem kesehatan, khususnya dalam aspek pembiayaan yang strategis dan berkelanjutan. Misalnya, alokasi dana untuk infrastruktur sering kali lebih dominan dibandingkan investasi jangka panjang seperti penguatan kapasitas tenaga kesehatan, integrasi sistem informasi kesehatan, atau peningkatan pelayanan primer yang promotif dan preventif. Dalam sebuah laporan BPK tahun 2023, disebutkan bahwa ada beberapa daerah kabupaten/kota di Aceh yang belum menggunakan dana Otsus secara maksimal untuk sektor kesehatan, meskipun beban pelayanan semakin meningkat.
Situasi geografis Aceh yang luas, dengan banyak daerah terpencil dan sulit dijangkau, juga memberi tantangan tersendiri. Biaya pelayanan kesehatan di daerah terpencil tentu jauh lebih tinggi, baik untuk pengadaan alat, transportasi pasien, maupun biaya logistik lainnya. Sistem pembiayaan nasional sering kali belum mempertimbangkan faktor ini secara proporsional. Akibatnya, fasilitas kesehatan di daerah terpencil menghadapi keterbatasan dalam menyediakan layanan yang setara dengan fasilitas di kota besar.
Masalah lain yang juga berkaitan erat dengan pembiayaan adalah soal keberlanjutan tenaga kesehatan. Banyak daerah di Aceh yang masih kekurangan dokter spesialis, bidan, dan perawat, terutama di daerah pegunungan dan pulau-pulau kecil. Pemerintah daerah memang telah berupaya melalui berbagai skema insentif daerah, namun bila tidak ditopang oleh sistem pembiayaan yang kuat dan terencana dengan baik, maka program insentif akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.
Namun demikian, tidak sedikit pula inisiatif positif yang patut diapresiasi. Di beberapa kabupaten, seperti Aceh Tengah dan Aceh Barat Daya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan layanan puskesmas dan penyediaan ambulans laut atau kendaraan 4WD untuk menjangkau daerah-daerah sulit. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi di Aceh juga mulai diarahkan untuk mendukung evaluasi dan perencanaan pembiayaan yang lebih berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk kesadaran kolektif bahwa sistem pembiayaan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus bersinergi dengan sistem informasi, tata kelola, manajemen SDM, hingga partisipasi masyarakat. Dalam beberapa forum nasional, isu harmonisasi pembiayaan antara pusat dan daerah juga terus dibahas, termasuk peluang untuk mengembangkan “capitation-based budgeting” atau “performance-based financing” yang lebih fleksibel dan mendorong efisiensi layanan.
Pembelajaran dari pandemi COVID-19 juga memberi pelajaran penting: bahwa ketahanan sistem kesehatan sangat bergantung pada kekuatan pembiayaannya. Di masa pandemi, banyak fasilitas kesehatan yang kewalahan karena ketidakpastian pembiayaan dan kurangnya cadangan dana darurat. Kini, saat dunia memasuki era post-pandemic, muncul kebutuhan untuk membangun sistem pembiayaan yang lebih antisipatif dan adaptif terhadap risiko kesehatan yang tak terduga di masa depan.
Dalam konteks Aceh, membangun sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan bukan semata soal memperbesar anggaran, tetapi juga memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan dengan efisien, tepat sasaran, dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ini memerlukan tata kelola yang akuntabel, transparansi dalam pelaporan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.
Kesimpulannya, pembiayaan kesehatan adalah jantung dari sistem kesehatan. Tanpa pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan, upaya peningkatan mutu layanan, pemerataan akses, dan perlindungan sosial kesehatan tidak akan berjalan optimal. Aceh, dengan segala keistimewaannya, memiliki peluang besar untuk menjadi model pembiayaan kesehatan daerah yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Namun untuk mewujudkan itu, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sinergi antarlembaga, dan keberanian untuk melakukan reformasi sistem secara menyeluruh.(*)
sumber SerambiNews.com