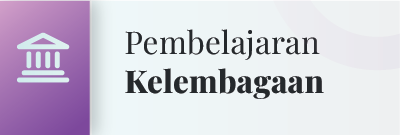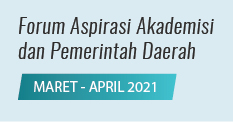Dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah antara lain mengarusutamakan inklusi sosial. Implikasinya, pemenuhan hak kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan seperti anak penyandang disabilitas perlu mendapat prioritas dalam kebijakan kesehatan nasional. Harian Kompas menyoroti hal ini (24/2/2025), dengan mengetengahkan rekomendasi Kertas Kerja Pembiayaan Kesehatan Anak Penyandang Disabilitas yang digagas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND), Save the Children Indonesia, serta Lembaga Analis dan Advokasi Kebijakan Publik (Elkape).
Menurut estimasi Riset Kesehatan Dasar 2018, terdapat hingga dua juta anak penyandang disabilitas di Indonesia. Sementara Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat prevalensi penyandang disabilitas penglihatan, pendengaran, dan berjalan pada anak berusia kurang dari 1 tahun adalah 1,2% dan pada anak berusia 5-17 tahun sejumlah 1,6%, tidak termasuk mereka yang memiliki hambatan mental dan intelektual.
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui program bantuan seperti Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan layanan terapi pada sentra-sentra Kementerian Sosial. Namun, kesenjangan capaiannya masih besar. Menurut Kementerian Sosial pada 2022 kurang dari 30% anak penyandang disabilitas menerima rehabilitasi.
Baca juga:Pemilu Inklusi
Kenyataan di lapangan menunjukkan penyediaan layanan kesehatan bagi kelompok penyandang disabilitas jauh dari memadai serta tidak merata di berbagai daerah. Keterbatasan anggaran pemerintah dan cakupan layanan BPJS Kesehatan menjadi kendala utama.
Kebutuhan biaya kesehatan bagi anak penyandang disabilitas memang tinggi. Studi berjudul "The Economic Costs of Childhood Disability" yang dilakukan Shahat dan Greco pada tahun 2021 di berbagai negara mengungkap biaya tahunan antara $450 hingga $69.500. Di negara-negara berkembang biayanya berkisar $500 hingga $7.500. Besarannya bervariasi bergantung pada jenis dan tingkat disabilitas anak.
Biaya di atas mencakup berbagai komponen layanan medis khusus. Termasuk di dalamnya biaya langsung medis untuk diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan penanganan komplikasi; serta biaya langsung non-medis, seperti transportasi ke fasilitas kesehatan, penyediaan alat bantu, maupun pelatihan khusus tenaga kesehatan. Di luar itu, masih terdapat biaya tidak langsung berupa hilangnya produktivitas orang tua ataupun tenaga pendamping yang merawat.
Di luar itu, terdapat pula kebutuhan perlindungan kesehatan anak berkebutuhan khusus lain, misalnya mereka yang mengalami kelainan darah, seperti talasemia. Yayasan Talasemia Indonesia mencatat pada 2021 terdapat 10.973 kasus. Biaya kesehatan anak dengan talasemia major, mencakup biaya transfusi darah dan terapi khelasi, diperkirakan mencapai Rp 300 juta setahun (Rahmah dan Makiyah, 2022).
Survei Kesehatan Indonesia 2023 juga menyodorkan fakta penting, yakni prevalensi tinggi anak penyandang disabilitas pada keluarga-keluarga berpendapatan rendah. Ini berarti anak penyandang disabilitas tergolong kelompok masyarakat dengan kerentanan ganda. Fakta ini sekaligus menjelaskan maraknya penggalangan dana, misalnya di platform donasi online, untuk biaya pengobatan dan pengasuhan anak penyandang disabilitas.
Maka, dalam konteks perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, hak kesehatan bagi anak penyandang disabilitas bukanlah pilihan, melainkan kewajiban negara. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang menegaskan hak setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
Biaya kesehatan anak penyandang disabilitas yang besar dan umumnya bersifat seumur hidup tidaklah mungkin ditanggung sendiri oleh keluarga. Perawatan medis rutin, terapi okupasi, alat bantu kesehatan, hingga kebutuhan rehabilitasi memerlukan sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Sementara itu, intervensi layanan kesehatan sejak usia dini amat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian, serta sekaligus menurunkan kebutuhan biaya kesehatan di masa depan.
Keberpihakan pemerintah diperlukan karena anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan ekstra. Mereka menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, baik dari segi finansial, geografis, maupun ketersediaan layanan medis yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Tanpa intervensi yang memadai, mereka akan semakin terpinggirkan, serta kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi aktif di masyarakat.
Keterbatasan Pembiayaan Pemerintah dan JKN
Saat ini, pembiayaan layanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas masih sangat bergantung pada alokasi anggaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan.
Namun, anggaran kesehatan nasional memiliki keterbatasan yang signifikan. Alokasi anggaran kesehatan berasal dari APBN (6%) dan APBD (10%), dimana sebagian besar digunakan untuk program kesehatan dasar serta penanggulangan penyakit menular. Cakupan penerima bantuan alat bantu Kemensos melalui program ATENSI masih terbatas. Lagi pula, model pembiayaan kesehatan bagi penyandang disabilitas bersifat seumur hidup, tidak boleh bergantung pada pola penganggaran tahunan pemerintah.
Sementara itu, BPJS Kesehatan menghadapi defisit keuangan yang terus berulang akibat tingginya klaim pelayanan kesehatan dibandingkan dengan penerimaan iuran. Kondisi ini membuat cakupan layanan bagi anak penyandang disabilitas tidak optimal. Terapi okupasi, rehabilitasi medis, serta alat bantu belum sepenuhnya dibiayai, sehingga banyak keluarga harus menanggung biaya secara mandiri.
Skema Pembiayaan Alternatif
Menyiasati besarnya kebutuhan biaya kesehatan anak penyandang disabilitas serta keterbatasan anggaran pemerintah dan JKN, maka diperlukan skema pembiayaan berkelanjutan yang tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Skema pembiayaannya ke depan perlu melibatkan peran sektor swasta dan masyarakat. Solusi yang dapat diterapkan adalah pembentukan badan khusus yang mengelola secara independen pooling fund dengan bersumber dari pemerintah, bantuan internasional, program CSR, sumbangan filantropi, maupun donasi publik.
Keberadaan badan khusus ini, akan melengkapi pola-pola pembiayaan yang telah ada, dengan berfokus pada pembiayaan kebutuhan medis spesifik seperti terapi okupasi, rehabilitasi, dan penyediaan teknologi asistif. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk subsidi langsung ataupun pemberian voucher kesehatan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan.
Pembangunan skema pembiayaan alternatif ini tidak hanya akan meningkatkan keberlanjutan layanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas, tetapi juga mengurangi beban keuangan negara. Kesehatan anak-anak penyandang disabilitas bukan hanya tentang hak individu, tetapi merupakan investasi bagi masa depan bangsa.